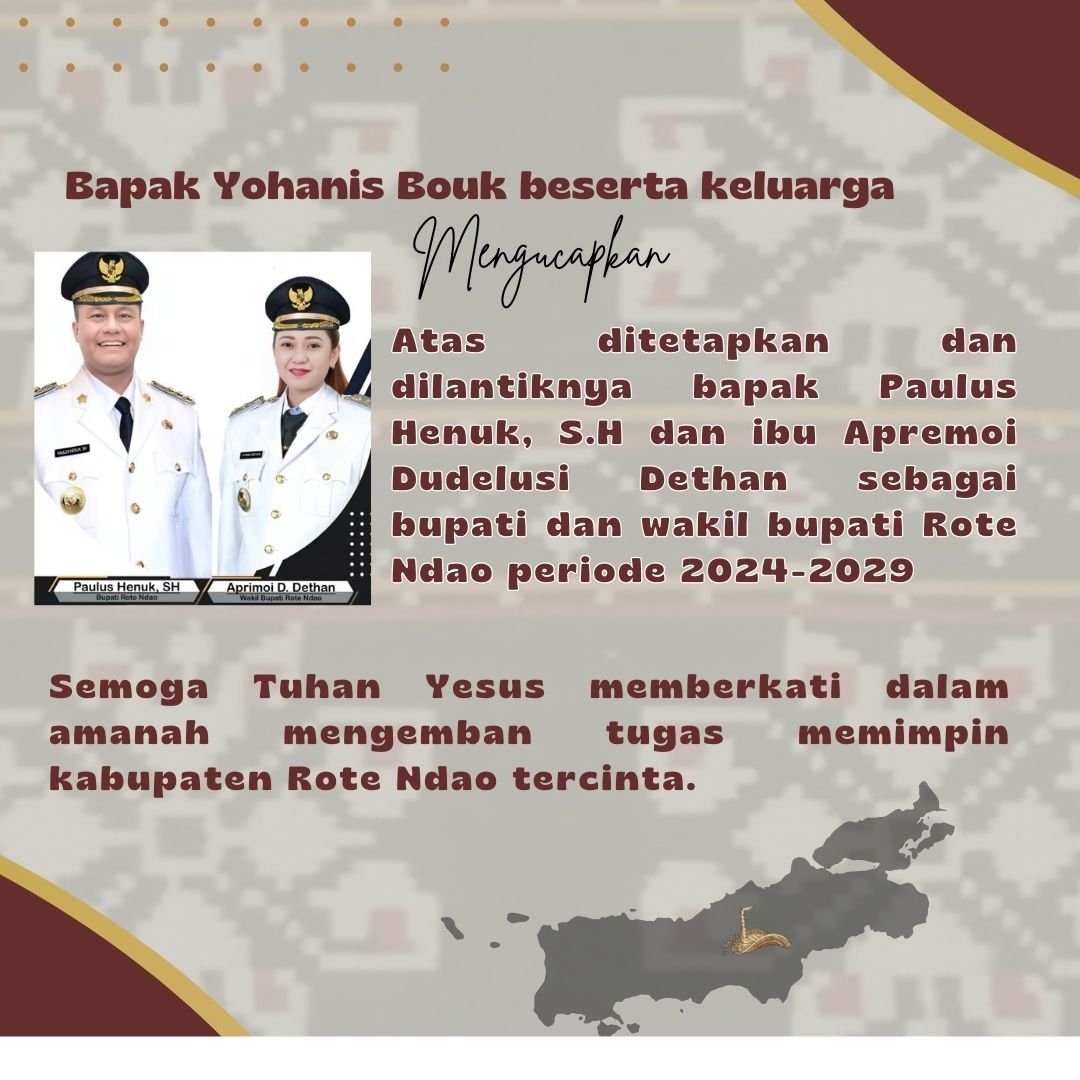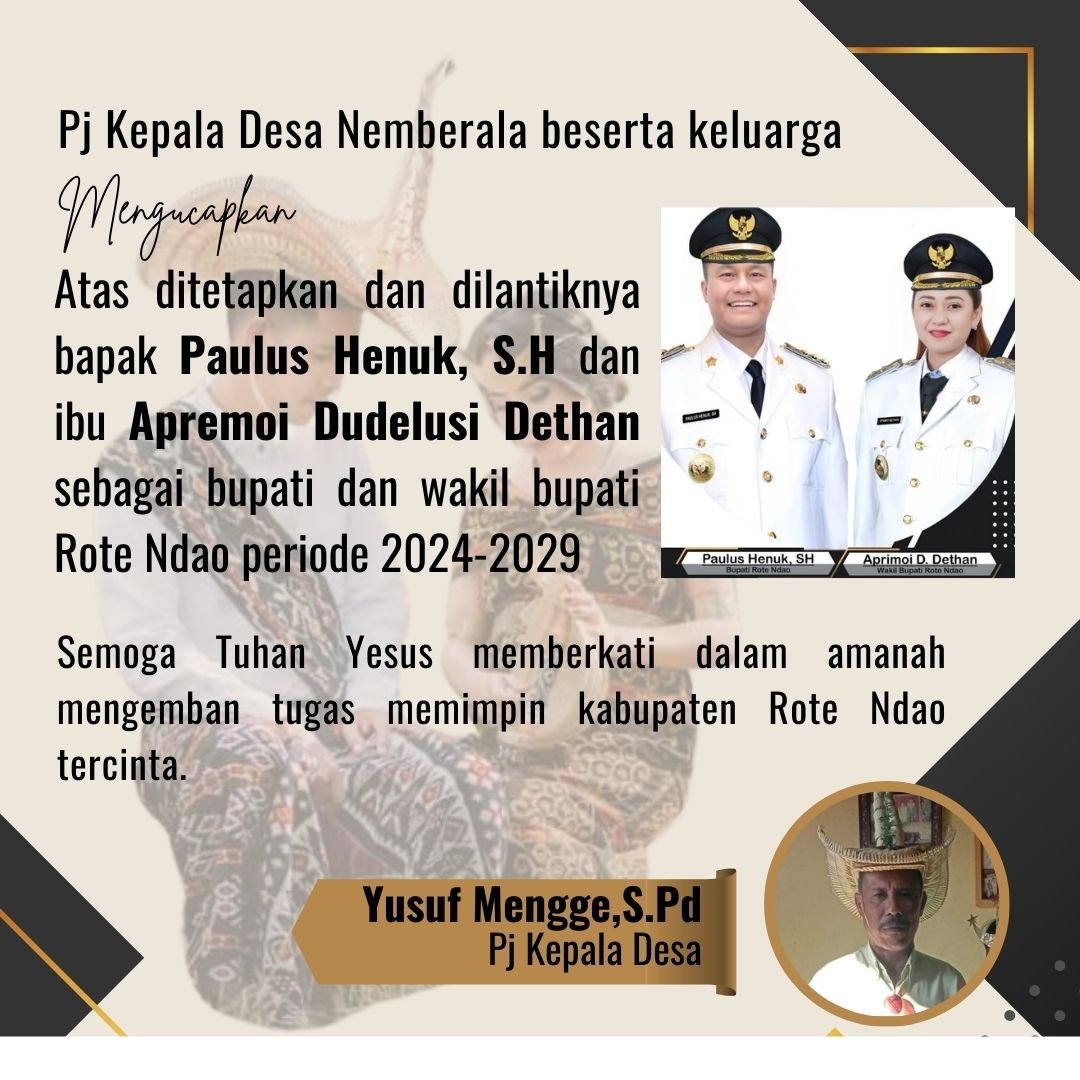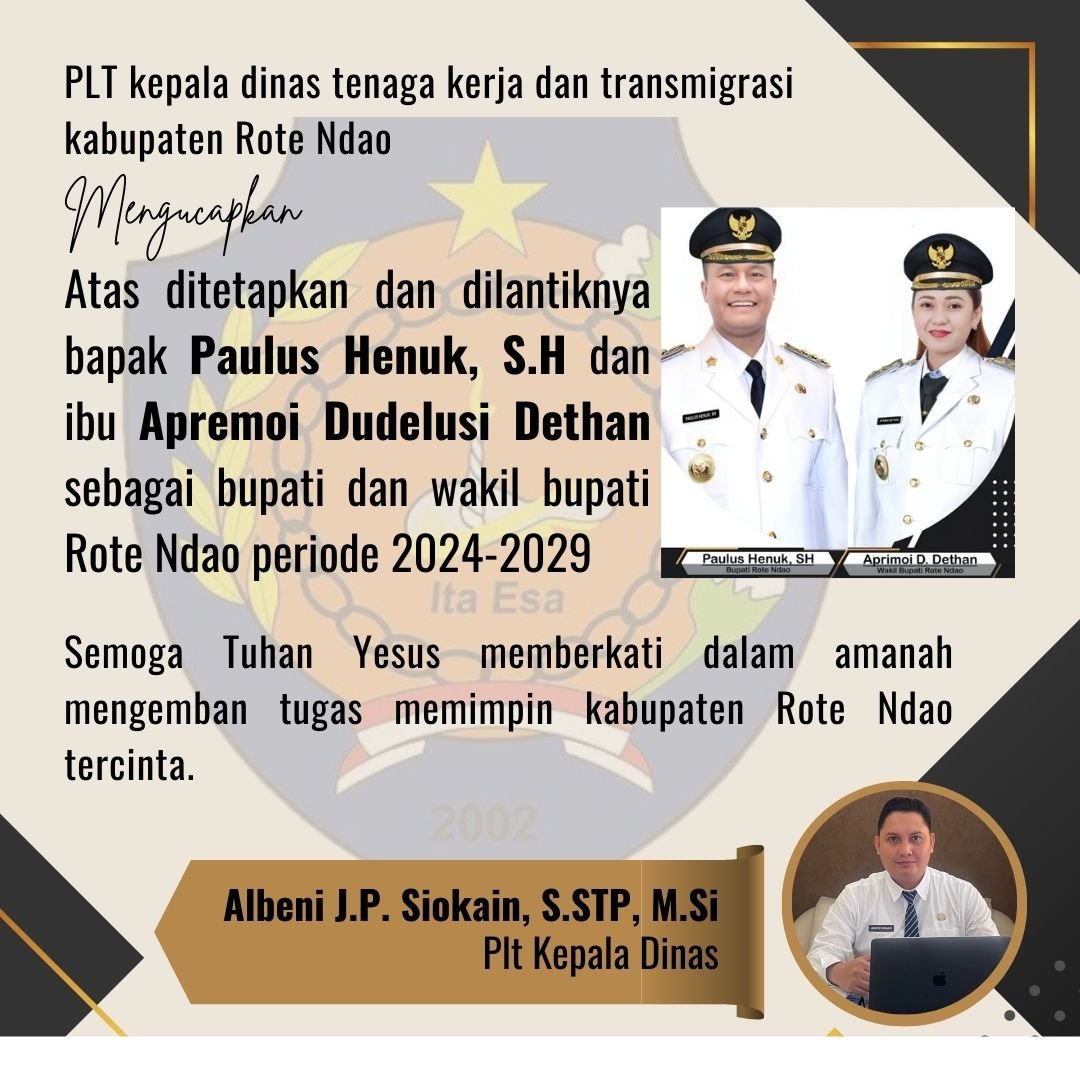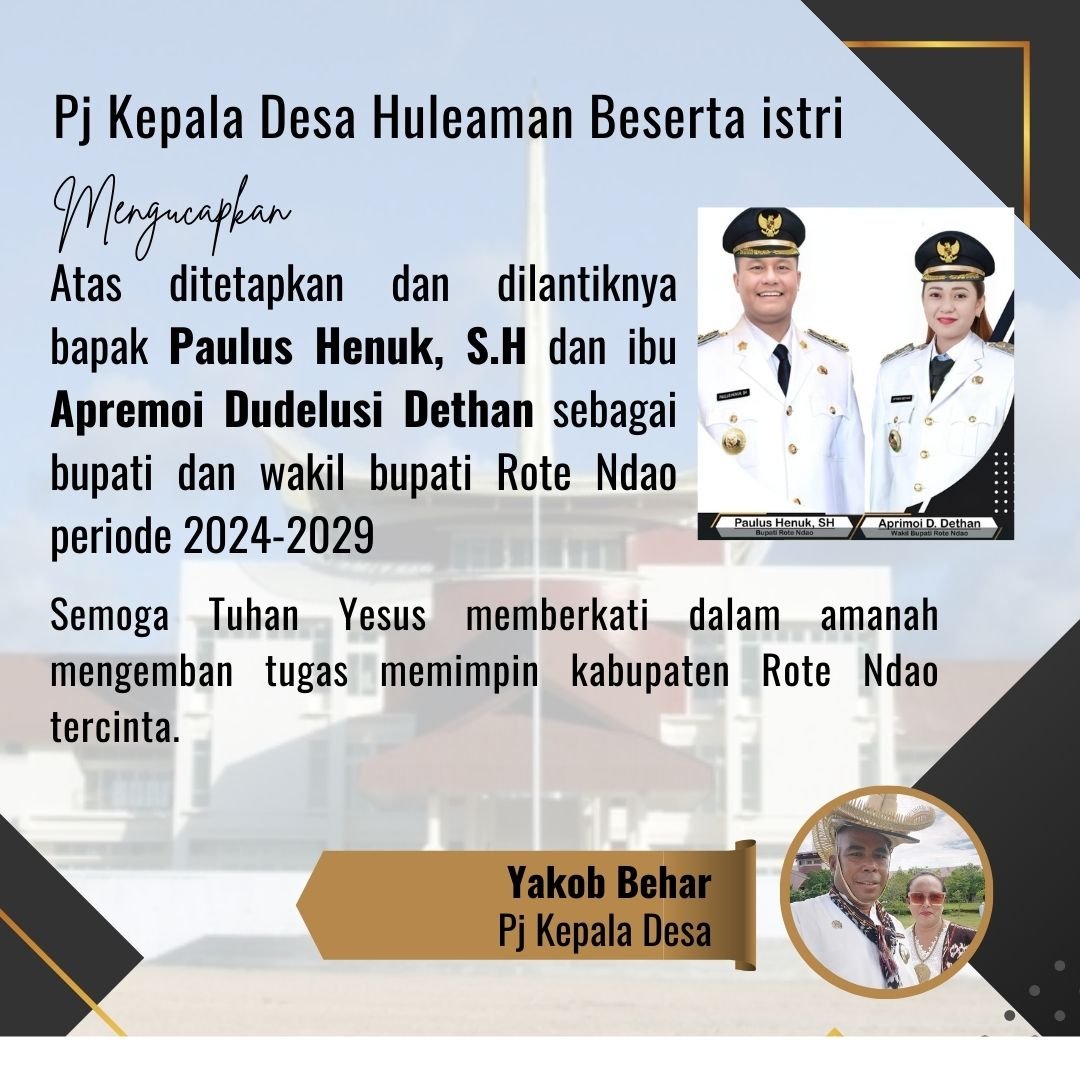Suara protes rakyat jelata terkait ‘bencana ekologis’ yang ditimbulkan oleh pelbagai ‘proyek pembangunan ekstraktif dan pariwisata’ tidak pernah ditanggapi secara serius. Meski peristiwa bencana alam begitu sering terjadi tersebab oleh pembangunan yang berciri destruktif terhadap alam itu, pemerintah ‘tetap nekat’ menerapkan skema pembangunan yang berwatak elitis dan sentralistis tersebut.
Padahal, kita semua tahu bahwa bumi ini hanya satu. Daya dukung bumi untuk memenuhi ambisi dan kerakusan manusia, sangat terbatas. Publik mondial sudah sadar akan ‘dosa ekologi’ yang telah diperbuat oleh manusia masa lalu. Bumi sangat rentan untuk menjadi planet yang sakit jika laju penghancuran terhadap bumi tak bisa diminimalisasi.
Salah satu aktivitas yang berpotensi ‘menurunkan sistem kekebalan bumi adalah penebangan hutan baik secara liar maupun secara legal. Bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan menjadi ancaman yang begitu telanjang ketika ‘hutan digubah’ seturut interes ekonomis dari negara dan para pemilik modal.
Kebijakan alih-fungsi hutan Bowosie-Nggorang seluas 400 hektar menjadi kawasan investasi bisnis pariwisata mewah, hemat saya bisa menjadi salah satu contoh teraktual bagaimana upaya ‘penodaan terhadap alam’ diterapkan demi melayani pemenuhan hasrat ekonomi kapitalistik tersebut.
Bagaimana mungkin di tengah gencarnya upaya ‘menyehatkan bumi’ melalui gerakan menanam pohon, Negara, melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) justru ‘memotong pohon’, menghancurkan hutan dengan segala keanekaragaman hayati di dalamnya? Coba bayangkan berapa banyak jenis pepohonan dan spesies hewan yang akan ‘dikorbankan’ dalam membangun pelbagai fasilitas bisnis pariwisata mewah di lahan seluas 400 hektar itu?
Beberapa elemen masyarakat sipil sudah memberikan pandangan kritis terkait rencana BPOLBF itu. Jika ‘cerita alih fungsi’ itu terjadi, maka potensi datangnya bencana seperti banji, tanah longsor, dan mengeringnya sumber air, bukan isapan jempol belaka. Kawasan Bowosie-Nggorang itu berada di ketinggian. Daerah itu menjadi semacam ‘penyangga’ sekaligus area tangkapan air. Kurang lebih 10 titik mata air di Labuan Bajo dan sekitarnya sangat bergantung pada ‘stok air’ yang mengendap di wilayah itu.
Aneh. Kita sering mengeluh soal ‘terbatasnya sumber air’ di kota ini. Ketika stok air yang dikelola oleh perusahaan negara terbatas, banyak warga yang memanfaatkan mata air alami yang sebagian besar ‘berasal’ dari Hutan Bowosie ite. Tetapi, tragisnya justru BPOLBF datang untuk ‘merusak’ lumbung air itu demi terlaksananya agenda menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super premium. BPOLBF begitu terpikat dengan penciptaan ‘cerita sukses’ percepatan pembangunan pariwisata dengan mengonversi hutan menjadi ‘destinasi wisata buatan (hand made destination).
Pertanyaannya adalah apakah ‘pembangunan destinasi wisata buatan’ itu, begitu mendesak dan vital sehingga harus mengorbankan ‘keutuhan alam’? Apakah dimensi keperawanan hutan dan ketersediaan air, tidak menjadi fokus perhatian kita? Mampukan BPOLBF ‘menciptakan’ sumber mata air dan aneka ragam spesies flora dan fauna’ yang baru? Apakah BPOLBF merupakan ‘agen perusak hutan yang legal’?